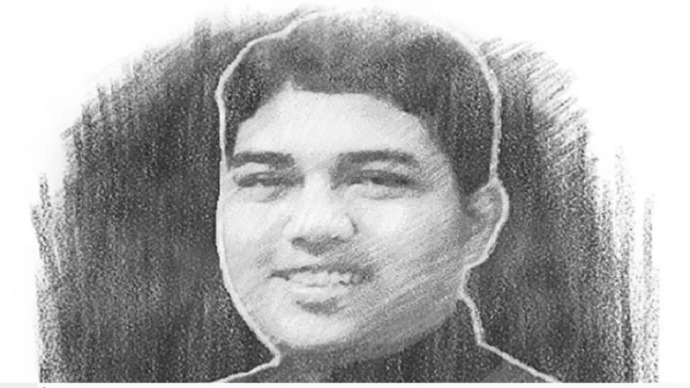ILMU pengetahuan dikembangkan untuk apa dan untuk siapa?, Pertanyaan ini memang sangat mudah untuk dijawab secara normatif, namun pada hakikatnya sangat sulit untuk direalisasikan peruntukannya. Ketika disodori pertanyaan seperti itu, dengan mudah kebanyakan orang pasti akan menjawab bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan peradaban manusia. Jawaban tersebut hal yang sangat idealis dan terdengar indah kalimatnya. Namun sebenarnya kosong makna alias klise.
Ide terkait pengembangan ilmu pengetahuan untuk membangun kesejahteraan atau peradaban ‘jauh panggang dari api’. Musababnya masih sangat jauh dengan kondisi realitasnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh dua hal yang sangat fundamental.
Pertama, masyarakat kita belum memiliki minat yang cukup untuk mengakses ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah produksi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum akademisi, ternyata lebih banyak didasari masalah-masalah administratif semata. Jadi, alih-alih sebagai niat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, guna meningkatkan kesejahteraan dan peradaban masyarakat. Namun justru terjebak pada angka akreditasi.
Akses Terhadap Ilmu Pengetahuan
Saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat berkembang. Hal tersebut memudahkan manusia untuk saling bertukar informasi. Dampak perkembangan teknologi informasi ini juga sangat berdampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Karena hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan atau akademisi, kemudian dapat disebarluaskan dalam bentuk berbagai macam jenis publikasi seperti buku, jurnal, prosiding, dan lain sebagainya.
Yang semuanya dapat dibagikan dan diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi seperti internet. Hampir semua publisher saat ini sudah melakukan publikasi secara digital, sehingga memudahkan untuk diakse oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun.
Mudahnya akses terhadap ilmu pengetahuan tersebut ternyata tidak serta merta membuat masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena minat masyarakat untk mengakses ilmu pengetahuan masih sangat rendah.
Masalah ini terutama disebabkan karena minat baca di masyarakat kita yang masih sangat rendah. Dan hal ini terjadi hampir pada semua tingatan generasi di Indonesia. Buktinya, Program of International Student Assessment (PISA) pada tahun 2019, menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara yang dilihat dari sisi minat membaca, yang artinya masyarakat Indonesia memiliki minat baca yang sangat rendah.
Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan kapitalisasi sistem pendidikan yang semakin mengkerdilkan tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia. Tak bisa dipungkiri, hingga saat ini salah satu problem klasik pendidikan di negara kita adalah terkait tingginya biaya pendidikan.
Masih terlalu banyak masyarakat yang terpaksa putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena alasan mahalnya biaya pendidikan.
Dengan adanya kondisi tersebut, lalu timbul pertanyaan bagaimana mungkin dengan minat baca yang rendah ditambah tingkat pendidikan yang juga rendah, masyarakat akan bisa berinteraksi dengan ilmu pengetahuan yang dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peradaban masyarakat itu sendiri?. Kalimat pertanyaan tersebut menggambarkan suatu kondisi ironi yang sangat kritis.
Ilmu Pengetahuan Berputar dalam Lingkaran Setan Akademisi
Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itulah makna dari akademisi.
demikian, bisa disimpulkan bahwa tugas utama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibebankan pada pundak para akademisi. Tentunya sekilas menjadi sebuah tugas yang sangat mulia karena ide utamnya dengan ilmu pengetahuan yang dikembangkan, maka nantinya masyarakat akan lebih sejahtera dan lebih beradab.
Namun, realitasnya justru beban yang sangat memberatkan bagi para akademisi adalah, ketika proses pengembangan ilmu pengetahuan tersebut masuk dalam ranah “administrasi” beban kinerja yang harus dilaporkan secara berkala per enam bulan, sebagai standarisasi beban kinerja para akademisi.
Hal ini tidak hanya dalam konteks kinerja individu, tetapi juga menyangkut lembaga mereka. Tentunya hal ini justru memaksa para akademisi untuk berlomba-lomba menjadi “seolah-olah produktif” dengan melakukan berbagai publikasi yang menjadi penanda kerja pengembangan ilmu pengetahuan.
Selain menjadi beban kerja, bukti publikasi juga bisa mengantarkan para akademisi untuk naik jabatan fungsional. Bahkan kinerja publikasi mereka juga akan membawa dampak pada kinerja lembaga, baik dalam konteks lembaga penelitian pemerintah, maupun universitas-universitas yang terbelenggu dalam administrasi akreditasi. Maka hal ini justru menimbulkan masalah baru, yaitu untuk meningkatkan kinerja penelitian dan publikasinya tidak jarang para akademisi terjebak pada tindakan-tindakan plagiat atau melakukan kecurangan-kecurangan lainnya (dilakukan oleh sebagian okmun-oknum akademisi).
Tuntutan kinerja pengembangan ilmu pengetahuan, di satu sisi memang bisa mendorong produktivitas kinerja penelitian dan publikasi. Hal ini menandakan bahwa ilmu pengetahuan menjadi semakin berkembang yang dapat diakses siapapun, kapanpun, dan dimanapun.
Tetapi target dari pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu para masyarakat ternyata masih memiliki minat yang rendah untuk mengakses ilmu pengetahuan tersebut. Maka ujung dari problematika ini membawa pada berputarnya distribusi ilmu pengetahun di tengah pusaran yang lebih mirip seperti lingkaran setan pada kalangan akademisi yang berambisi memenuhi kinerja pengembangan ilmu pengetahuan (hanya sebatas makna administratif).
Produk ilmu pengetahun yang dikembangkan oleh seorang akademisi tidak akan diakses oleh masyarakat, melainkan akan dikonsumsi kembali oleh akademisi yang lain untuk dijadikan bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya. Sehingga menyebabkan ilmu pengetahuan tidak menemui target sasaran yang digagas secara filosofis terkait peruntukannya, yaitu peningkatan kesejahteraan dan peradaban masyarakat.
Ilmu pengetahuan ternyata justru menemui jalan buntu dan pada akhirnya terjebak pada kondisi ekslusivitas yang hanya dikonsumsi oleh para akademisi untuk memenuhi “syahwat akademik” mereka dalam meningkatkan kinerja dan kenaikan jabatan fungsional.
*) Ardli Johan Kusuma, Dosen Magister Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta