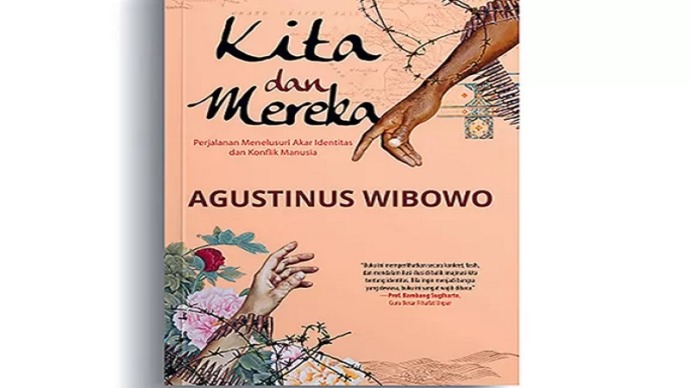Sebagai ilusi, identitas dapat menjadi berkah sekaligus kutukan. Buku ini menyajikan banyak sekali contoh petaka identitas yang menghiasi jatuh bangunnya peradaban-peradaban besar dunia, tetapi untungnya juga memuat cara meloloskan diri dari kutukan identitas tadi.
BUKU yang tampak ambisius ini sebenarnya dipantik oleh satu pertanyaan sederhana tapi fundamental: mengapa miliaran manusia yang secara anatomi-biologis sama mesti terbelah menjadi gugus ”kita” dan ”mereka”?
Bukan semata soal segregasi bahasa, dikotomi ”kita” dan ”mereka” ternyata memiliki akar silsilah yang sangat personal dalam diri manusia: ketakutan. Ketakutan merupakan bahan bakar utama manusia yang menyalakan obsesi besar mereka dalam membangun tembok-tembok pembatas dan pelindung.
Kita bisa mengambil banyak sampel dari peradaban-peradaban besar di dunia. Tiongkok membangun tembok raksasa untuk membendung ancaman suku nomad Mongol dari sisi utara. Pada abad ke-5 M, Persia membangun Tembok Ular Merah sepanjang 200 kilometer dari Laut Kaspia hingga Laut Hitam untuk menghalau serangan nomad Hun dari padang Eurasia.
Pembangunan tembok-tembok pertama di dunia ditemukan di Mesopotamia. Itu terjadi sekitar 11.000 tahun lampau ketika manusia mulai mendomestikasi tanaman dan melahirkan peradaban agrikultur. Di titik ini, sebetulnya bukan hanya tanaman atau hewan yang terjinakkan, melainkan ketakutan juga ikut terlembagakan secara sosial.
Dengan tepat penulis buku ini menggambarkan bahwa pembangunan tembok bertaut erat dengan ketakutan universal manusia akan kehilangan hal-hal yang dianggap berharga. Semakin banyak hal berharga yang kita miliki, sebesar itu pula kurva rasa takut kita untuk kehilangan. Dan pada gilirannya, semakin tebal pula hasrat kita untuk mencari rasa aman (halaman 28–30).
Tembok-tembok fisik yang tampak kukuh dan angkuh itu pada hakikatnya merupakan perwujudan infrastruktur dari tembok-tembok tak kasat di dalam otak kita. Otak manusia dirancang untuk menerima rasa aman lebih banyak daripada rasa takut. Tidak salah jika Abraham Maslow menempatkan rasa aman di tangga kedua dalam piramida lima kebutuhan dasar manusia.
Riset-riset psikologi perkembangan telah lama menunjukkan bahwa bayi cenderung mau didekap dan digendong siapa saja sampai usia 6 bulan. Sejak usia 6 bulan –atau bahkan sedikit lebih awal dari ini– otak bayi mulai mengaktifkan sensor rasa takutnya kepada orang asing.
Dalam Child Development 6E (2017), Elizabeth B. Hurlock menyebutkan bahwa bayi pada usia 6 bulan sudah mampu mengenali siapa saja anggota keluarga yang dapat memenuhi rasa amannya. Sehingga ia cenderung akan menolak dan menangis jika tiba-tiba digendong oleh orang asing yang belum terbukti dapat mendatangkan rasa aman kepadanya.
Di titimangsa itulah segregasi antara ”kita” dan ”mereka” mulai terinstal di dalam perangkat otak manusia. Kondisi psikologis itu selanjutnya dengan mudah menjadi pupuk bagi bersemainya identitas kelompok, marga, suku, hingga bangsa.
Namun, seperti diwartakan buku ini, berbagai macam kategori identitas yang kita punya, yang kita anggap benar dan kerap kali kita bela mati-matian, sebenarnya adalah ilusi karena ia terbentuk dari perca-perca subjektivitas yang terus berubah dan bisa saling bertumpang-tindih satu sama lain.
Sebagai ilusi, identitas dapat menjadi berkah sekaligus kutukan. Buku ini menyajikan banyak sekali contoh petaka identitas yang menghiasi jatuh bangunnya peradaban-peradaban besar dunia, tetapi untungnya juga memuat cara meloloskan diri dari kutukan identitas tadi. Agustinus Wibowo, harus diakui, sangat piawai dalam memilin narasi.
Satu-satunya hal masygul dari buku ini adalah ketidakjelasan penempatan rujukan narasi antropologis masa lalu yang berjarak cukup jauh dari pengalaman penulisnya. Ini penting dijernihkan karena selincah apa pun Agustinus Wibowo menulis buku tebal ini, ia tetaplah pelancong yang tidak mungkin disejajarkan otoritasnya dengan Jared Diamond maupun Yuval Harari dalam mengemas data antropologi ataupun fakta sejarah. (*)
—
Judul: Kita dan Mereka: Perjalanan Menelusuri Akar Identitas dan Konflik Manusia
Penulis: Agustinus Wibowo
Penerbit: Mizan, Bandung
Cetakan: II, Maret 2024
Tebal: 669 halaman
ISBN: 978-602-441-338-5
—
*) NAUFIL ISTIKHARI, Alumnus Magister Psikologi UGM dengan minat utama mind, brain and performance