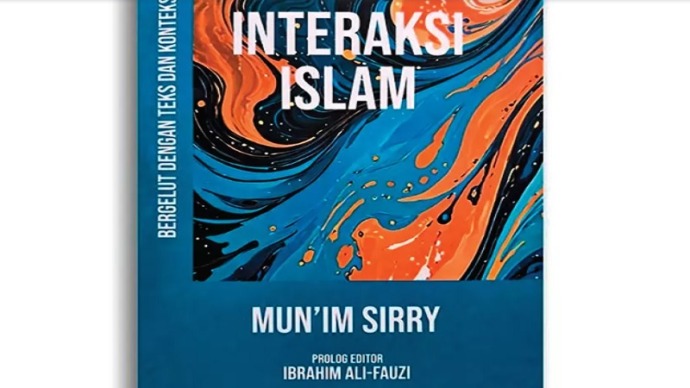Dua belas esai dalam buku ini merupakan serangkaian argumen yang cenderung ”negosiatif” lengkap dengan gaya argumentasi ilmiah yang runut, sistematis, dan kompleks.
ROBERT W. Hefner dalam karyanya, Islam and Citizenship in Indonesia: Democracy and the Quest for an Inclusive Public Ethic (2024), menyebut kelompok intelektual Islam kritis di awal reformasi di Indonesia sebagai ”systematic- eclecticism” (bab 4).
Di buku yang sama, Hefner mengaku terinspirasi dari salah satu antropolog kenamaan, Talal Asad, dengan gagasan terkenalnya mengenai ”Islam tradisi diskursif” bahwa wacana Islam terbentuk dalam watak yang heterogen dan meninggalkan wataknya yang homogen.
Islam sebagaimana bayangan Asad merupakan agama dinamis. Interaksinya dengan realitas politik, sosial, budaya, dan sistem keyakinan lain tak terelakkan. Sebagai ”agama historis”, Islam merupakan sebuah ”sistem doktrin” yang juga diasuh oleh sejarah.
Itulah mengapa kesarjanaan revisionis yang juga diakui Mun’im Sirry sendiri memiliki kesamaan pandangan yang cenderung menyebut Islam sebagai sebuah agama yang terbentuk secara ”gradual” dalam mekanisme sejarah. Sebelum kemudian menemukan bentuk ”formalnya” sebagaimana yang sampai pada kita sekarang.
Namun, ihwal pembentukan Islam awal yang gradual itu bukan menjadi perhatian utama Mun’im dalam karya terbarunya, Interaksi Islam: Bergelut dengan Teks dan Konteks (2024).
Diskusi mengenai kontroversi kemunculan Islam awal itu dapat ditemui dalam dua buku sebelumnya, Kemunculan Islam dalam Kesarjanaan Revisionis (2017) dan Rekonstruksi Islam Historis (2021). Dua karya Mun’im yang paling banyak membuat saya mengernyitkan dahi.
Bagi saya, dua belas esai dalam buku ini (termasuk pengantar) merupakan serangkaian argumen yang cenderung ”negosiatif” lengkap dengan gaya argumentasi ilmiah yang runut, sistematis, dan kompleks. Saya sebut negosiatif karena pendekatan yang didiskusikan dia dalam buku ini lebih banyak mengupayakan suatu kemungkinan membangun dialog lintas agama berdasar artikulasi teks dan konteks dalam lintasan panjang sejarah agama ini.
Kesarjanaan klasik hingga modern dielaborasi dengan sangat detail dan juga rumit. Buku ini merupakan bentuk afirmatif argumen-argumen hubungan lintas agama sebagaimana kerja-kerja ”intelektual-pluralis” di masa lalu. Hal itu misalnya tecermin di bagian ketiga dan keempat buku ini (hal 125 dan 163).
Di bagian-bagian tersebut, Mun’im berupaya mendudukkan kritik Alquran terhadap agama lain, atau yang dalam tesisnya disebut sebagai retorika polemik kitab suci itu, di dalam spektrum ”etis” penafsiran para intelektual muslim modern sebagai suatu upaya menjawab tantangan terkini masyarakat muslim.
Alih-alih menemukan cara kesarjanaan revisionis ”menelanjangi” Islam secara kontroversial, buku ini justru merupakan salah satu karya yang dalam hemat saya layak disodorkan kepada masyarakat muslim secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum.
Sebagai satu ikhtiar dalam upaya mendengungkan kembali argumen pluralisme agama yang telah cukup lama hiatus ke panggung wacana Islam di Indonesia. Artinya, elaborasi mendalam di dua belas esai buku ini cukup reliabel untuk dijadikan semacam handbook bagi mereka yang tertarik dengan isu-isu seputar hubungan lintas agama.
Namun, argumen negosiatif itu jangan dibaca sebagai tanda ”pertobatan” Mun’im. Saya justru melihat di tengah argumentasi-argumentasi kontroversial Mun’im di banyak karyanya, argumen ”proporsional” dia dalam buku ini nyatanya tidak cukup mampu menyembunyikan bumbu-bumbu kritik historisnya yang masih saja tajam dan menusuk.
Hal inilah yang justru menjadikan suatu gaya unik tersendiri dari tipe kesarjanaannya, yang sepenuhnya ”distingtif” dengan tipe intelektual muslim modern sebagaimana para pendahulunya.
Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Mun’im cenderung lebih piawai dalam mendiskusikan teks-teks dalam khazanah Islam lengkap dengan fitur historisnya, dengan dua gaya (meminjam tipologi Kim Knott) as insider dan as outsider sekaligus.
Kepiawaiannya itu misalnya tecermin di dua bagian terakhir buku ini, yang lagi-lagi gaya ”gugatan” dia terlihat ketika ia mempertanyakan ”anggapan” bahwa salafisme-puritan merupakan ”musuh” dari sufisme-mistik, nyatanya salafisme bukanlah gerakan yang tunggal (hal 323).
Yang kemudian ditutup dengan semacam ”saran akademik” Mun’im di bagian akhir buku ini. Dia memberikan semacam gambaran ke arah mana tren kontemporer semaraknya studi Alquran, yang didekati dengan beragam disiplin ilmu, tidak terbatas pada pendekatan tafsir belaka (hal 363).
Saya teringat ketika Mun’im Sirry menerbitkan buku Rekonstruksi Islam Historis (2021). Sebagian kalangan menilai posisi dia dalam peta kesarjanaan revisionis (dianggap) sebagai representasi kesarjanaan yang ”moderat” di antara dua kelompok kesarjanaan revisionis skeptis dan revisionis simpatik.
Sebab, sikap intelektualnya dalam buku itu memang cukup representatif untuk dikatakan bahwa dia berusaha memberikan argumen ”jalan tengah” di antara dua kutub revisionis dalam kesarjanaan Barat.
Sebaliknya, saya justru masih percaya pada sikap intelektual Mun’im jika didudukkan dalam lanskap intelektual muslim Indonesia, mungkin merupakan satu-satunya prototipe kesarjanaan progresif-liberal yang ”kafah” dan tetap konsisten untuk menolak ”murtad” dari tipe intelektual semacam itu. Sebagaimana kita rasakan begitu ”asyiknya” kebisingan kelompok yang disebut Hefner (2024) sebagai systematic-eclecticism di awal reformasi itu.
Saya menyebut istilah ”murtad” untuk memberikan semacam penjelasan bahwa ada tipe kesarjanaan liberal-Islam dalam perkembangan intelektual Islam di Indonesia mutakhir yang dianggap melakukan ”pertobatan intelektual”.
Namun, alih-alih setuju dengan predikat ”intelektual yang bertobat” itu, saya lebih suka menyebut mereka sebagai sekelompok intelektual yang memilih untuk ”murtad” dari predikat intelektual sejati, atau apa yang disebut Antonio Gramsci sebagai intelektual organik. Bagi saya, Mun’im sama sekali tak tergoda untuk murtad. Dia justru memilih teguh pada ”keimanan” intelektualnya. (*)
Judul buku : Interaksi Islam: Bergelut dengan Teks dan Konteks
Penulis : Mun’im Sirry
Penerbit : Suka Press
Terbit : Pertama, Oktober 2024
Jumlah : xiv + 390 halaman
ISBN : 978-623-7816-93-5
*) ADIB KHAIRIL MUSTHAFA, Mahasiswa Doktor Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta