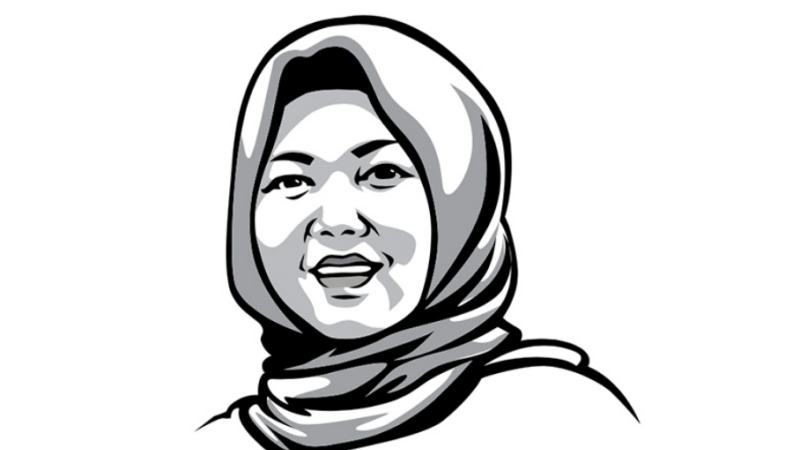KEKERASAN terhadap pengawas pilkada makin banyak. Contohnya kasus
yang dialami Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Genteng, Banyuwangi, 11
November lalu. Panwascam perempuan itu mendapatkan kekerasan verbal dari
pendukung pasangan calon (paslon) ketika melakukan kerja pengawasan. Videonya
viral.
Kasus di Banyuwangi tersebut
hanyalah satu di antara 31 kasus lainnya. Mengapa bisa terjadi?
Tampaknya, variabel penegakan
protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kampanye menjadi salah satu faktor pendukung dari
kekerasan terhadap pengawas pilkada. Di satu sisi, tanggung jawab pengawas kian
berat. Di sisi lain, peserta pilkada belum sepenuhnya beradaptasi. Sebab, pada
pilkada sebelumnya tidak ada aturan seperti itu.
Tahapan kampanye yang didorong
dengan daring tidak jadi pilihan. Pertemuan terbatas dan tatap muka terus
meningkat. Selama 50 hari berjalannya kampanye, Bawaslu mencatat 17.738
kampanye pertemuan tatap muka. Dari jumlah itu, pengawas pilkada menertibkan
1.444 kasus kampanye yang melanggar protokol kesehatan.
PKPU 13/2020 tegas mengatur bahwa
kampanye tatap muka terbatas dengan jumlah 50 orang yang hadir. Jika paslon
melanggar, pengawas pilkada mengeluarkan imbauan dan surat peringatan. Apabila
tidak diindahkan, pengawas berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pencegahan
Covid-19 dan kepolisian untuk membubarkan. Pada saat ketegasan pengawas pilkada
ditunjukkan, saat itulah gesekan di lapangan bisa terjadi.
Situasi di lapangan tak semudah
teori. Dibutuhkan keberanian dan tanggung jawab besar untuk menegakkan protokol
kesehatan. Ketika pengawas pilkada menjalankan prosedur di tengah suasana
kampanye yeng heorik, di situlah potensi untuk menghalang-halangi kerja petugas
terjadi. Ada pengawas pilkada yang mengalami kekerasan verbal, pengusiran,
sampai kekerasan fisik.
Variabel lainnya adalah efek echo
chambers pilkada. Apalagi, misalnya, jika kontestasi hanya diikuti dua paslon.
Ketika paslon yang didukung ditindak tegas, pendukungnya akan berupaya mencari
kesalahan lawan untuk kemudian memunculkan tuduhan ketidakadilan kerja
pengawasan.
Yang terbentuk bukan pola
kesadaran, tetapi menyalahkan kerja pengawas pilkada. Yang diserang adalah
penyelenggara. Terbukti, ketika dugaan intimidasi panwascam di Banyuwangi
diangkat sebagai berita di laman resmi media sosial, pola echo chambers tampak
terlihat dengan nyata saat pendukung paslon melakukan serangan balik di media
sosial.
Ibarat pepatah, gajah di depan
mata tak kelihatan, tetapi semut di seberang lautan tampak dengan jelas.
Kesadaran diri dan kelompoknya tidak tampak, tapi kesalahan orang lain
direproduksi secara terus-menerus yang terlihat ke permukaan. Kerja pengawasan yang
berintegritas akhirnya mendapatkan bullying dan bahkan kekerasan dari massa
pendukung.
Variabel ketiga adalah adanya
kontestasi yang sengit dan menganggap pilkada sebagai perang yang harus
dimenangi. Lagu lama di setiap kontestasi dengan melibatkan massa pendukung
fanatik yang ingin memenangkan paslonnya tampak sebagaimana rumput kering yang
mudah sekali dibakar untuk provokasi.
Pola kekerasan pada masa
kampanye, jika tidak dicegah, akan terus meningkat sampai pemungutan suara dan
pasca pemilihan. Pengalaman pilkada 2015 dan 2018 lalu, saluran kekerasan yang
didiamkan bisa memuncak saat pasca pemilihan dengan selisih suara yang tipis.
Di Tuban pernah terjadi pembakaran gedung KPU pada 2015 oleh massa pendukung karena
selisih suara yang tipis.
Perempuan Pengawas Jadi Korban
Pola intimidasi dan kekerasan
banyak menimpa pengawas ad hoc, yakni pengawas di tingkat kecamatan, desa, dan
pengawas tempat pemungutan suara (TPS). Itu membuktikan bahwa makin dekat
dengan pemilih, tensi singgungannya makin panas. Suhu politiknya akan kian
meningkat. Pengawas pilkada dituntut tak hanya membawa alat kerja, tapi juga
sekeranjang keberanian untuk menegakkan aturan.
Kekerasan yang terungkap ke
publik adalah fenomena gunung es di tengah banyaknya intimidasi kepada pengawas
pilkada. Penelitian saya pada 2019 tentang keterpenuhan 30 persen perempuan
pengawas pemilu yang diterbitkan Bawaslu RI menemukan bahwa perempuan pengawas
di Jawa Timur kerap mengalami ancaman dan intimidasi saat melakukan kerja
pengawasan.
Pengakuan dari perempuan pengawas
itu juga menjadi batu sandungan terkait tingkat partisipasi politik perempuan.
Alih-alih untuk dapat mencukupi kuota 30 persen, untuk berani mengawasi saja,
sudah terintimidasi oleh aktor-aktor yang berkepentingan memenangi kontestasi.
Relasi kuasa aktor di tingkat
lokal di daerah yang tertutup memang tidak ramah terhadap perempuan pengawas.
Secara gender sudah mengalami marginalisasi. Maka, saat melakukan kerja
penegakan aturan; pola ancaman, intimidasi, dan kekerasan verbal dilakukan
untuk menyurutkan langkah petugas pengawasan. Padahal, kalau mau berpegang pada
aturan, kerja menghalangi aturan bisa dijerat pidana. Sebagaimana dalam pasal
198A UU 10/2016. Aturan yang tegas itu akan terwujud jika didukung aparat
keamanan.
Perlindungan Aparat Keamanan
Negara tidak boleh kalah dengan
premanisme. Ancaman, teror, dan intimidasi terhadap demokrasi harus kita lawan
sehormat-hormatnya. Mimpi membangun demokrasi substansial secara nasional harus
dimulai dari tingkat TPS, desa, dan kecamatan. Ini garda depan demokrasi. Kalau
garda depannya remuk karena intimidasi, membangun demokrasi substansial hanya
jadi mimpi.
Untuk itulah, aparat keamanan
perlu hadir dan bersama pengawas pilkada di tingkat pengawas ad hoc melakukan
kerja pengawasan. Perlindungan dan keamanan yang kuat akan turut membantu
pengawas pilkada menjalankan kerja-kerja aturan.
Kerja pengawasan sesuai aturan
akan menjadi salah satu cara menyelamatkan jiwa masyarakat di tengah
pelaksanaan pilkada saat pandemi. Kita memang sedang bertaruh besar dan
pertaruhan ini harus dimenangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. (*)
(Nur Elya Anggraini, adalah Anggota
Bawaslu Provinsi Jawa Timur)