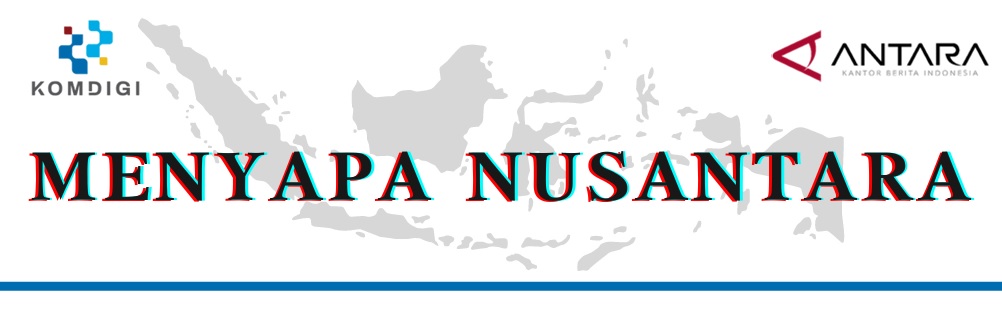 Indonesia memasuki usia 80 tahun kemerdekaan pada Agustus 2025. Delapan dekade bukanlah waktu yang singkat, melainkan perjalanan panjang sebuah bangsa menuju cita-cita yang diikrarkan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum.
Indonesia memasuki usia 80 tahun kemerdekaan pada Agustus 2025. Delapan dekade bukanlah waktu yang singkat, melainkan perjalanan panjang sebuah bangsa menuju cita-cita yang diikrarkan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum.
Peringatan 80 tahun kemerdekaan ini menjadi momentum refleksi: sudahkah janji kemerdekaan benar-benar hadir dalam kehidupan setiap warga?
Kabar baik datang memperkuat perayaan ini. Pada 25 Juli 2025 yang lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru, tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini turun dari 9,03 persen pada Maret 2024.
Penurunan tampak kecil, tetapi tetap signifikan di tengah ketidakpastian global, harga pangan yang bergejolak, risiko resesi di negara maju, hingga dampak perubahan iklim yang makin nyata. Indonesia berhasil menunjukkan daya tahan ekonomi sekaligus kemampuan melindungi masyarakatnya.
Lebih jauh, untuk pertama kalinya, BPS merilis angka kemiskinan ekstrem nasional. Dengan mengadopsi spatial deflator, alat untuk mengoreksi perbedaan harga antarwilayah yang lebih presisi dan selaras dengan rekomendasi internasional, termasuk Bank Dunia.
Hasilnya, penduduk miskin ekstrem pada Maret 2025 turun menjadi 0,85 persen atau 2,38 juta orang, dari 0,99 persen (2,78 juta orang) pada September 2024. Capaian ini memberi pesan penting, reformasi sosial dan ketahanan ekonomi kita bukan sekadar jargon, melainkan hasil nyata dari upaya bersama.
Namun, di balik angka yang menurun, penting diingat bahwa statistik bukanlah sekadar angka. Setiap persen yang berkurang mewakili ratusan ribu keluarga yang berhasil keluar dari jerat kemiskinan, tetapi juga mengingatkan bahwa masih ada puluhan juta warga yang hidup dalam keterbatasan.
Itulah mengapa, dalam perayaan 80 tahun Indonesia merdeka, capaian ini bukan hanya alasan untuk berbangga, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kolektif yang masih besar.
Membaca Data dengan Bijak
Sering kali angka kemiskinan disalahpahami publik. Garis Kemiskinan nasional Maret 2025 sebesar Rp609.160 per kapita per bulan kerap dipersepsikan seolah-olah orang miskin hanya hidup dengan Rp20 ribu per hari. Padahal, garis ini berlaku untuk rumah tangga. Rata-rata rumah tangga miskin beranggotakan 4,72 orang, sehingga kebutuhan minimumnya setara Rp2,87 juta per bulan.
Lebih dari itu, pola pengeluaran rumah tangga juga sangat bervariasi. Biaya sekolah anak atau pengobatan anggota keluarga bisa jauh lebih besar dibanding kebutuhan anggota lain.
Menyederhanakan kemiskinan menjadi sekadar angka tunggal tidak hanya keliru, tetapi juga menutup mata dari kerentanan nyata yang dihadapi keluarga miskin. Pemahaman publik yang lebih baik terhadap data akan membantu mendorong empati sekaligus kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Lebih jauh, membaca data kemiskinan juga menuntut kita melihat dimensi lain yang kerap luput dari perhatian. Kemiskinan tidak semata-mata soal pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Banyak keluarga yang secara statistik berhasil keluar dari garis kemiskinan, tapi tetap menghadapi beban berat dalam hal kualitas pendidikan anak, akses air bersih, perumahan layak, serta jaminan kesehatan. Mereka disebut kelompok rentan, keluar dari kemiskinan hari ini, tetapi dengan sedikit guncangan ekonomi atau bencana alam bisa kembali jatuh miskin.
Dalam konteks inilah, pencapaian penurunan angka kemiskinan perlu dibarengi dengan penguatan fondasi kesejahteraan jangka panjang. Akses pendidikan yang lebih merata, misalnya, akan menentukan kemampuan generasi berikutnya memutus rantai kemiskinan.
Demikian pula, penciptaan lapangan kerja layak dengan jaminan perlindungan sosial akan menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya keluar dari kemiskinan secara sesaat, tetapi benar-benar naik kelas. Angka statistik menjadi penting, tetapi jauh lebih penting adalah memastikan transisi dari “keluar dari kemiskinan” menuju “masuk ke dalam kesejahteraan yang berkelanjutan.”
Selain itu, di balik tren nasional, terdapat dinamika yang berbeda antarwilayah. Kemiskinan perkotaan justru sedikit naik, dari 6,66 persen pada September 2024 menjadi 6,73 persen (11,27 juta orang) pada Maret 2025. Ketergantungan pada pasar, stagnasi upah, serta dominasi pekerjaan informal —59,40 persen angkatan kerja perkotaan per Februari 2025— membuat rumah tangga miskin di kota lebih rentan.
Penurunan tingkat hunian hotel, misalnya, tidak hanya berdampak pada industri pariwisata formal, tetapi juga memukul pedagang kaki lima, pengemudi ojek daring, hingga usaha mikro di sekitarnya. Pemulihan makroekonomi belum sepenuhnya dirasakan di jalanan perkotaan.
Sebaliknya, perdesaan menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2025 mencapai 123,45, menandakan bahwa pendapatan petani lebih besar daripada biaya produksinya. Bagi desa, yang selama ini menjadi kantong utama kemiskinan, peningkatan kesejahteraan petani adalah kabar baik. Ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat ketahanan pangan dan akses pasar di perdesaan mulai membuahkan hasil.
Meski ada perbaikan, pekerjaan rumah masih sangat besar, terutama di wilayah timur Indonesia. Di Papua Pegunungan, lebih dari 30 persen penduduk masih hidup miskin. Fakta ini menegaskan bahwa pendekatan seragam tidak cukup. Indonesia membutuhkan pendekatan berbasis wilayah (place-based approach), yang mempertimbangkan kondisi lokal, dari akses jalan dan listrik, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga keterhubungan ke pasar.
Usia 80 tahun merdeka seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat keberpihakan kebijakan terhadap wilayah yang selama ini tertinggal.
Data Sebagai Fondasi
Ke depan, penguatan data menjadi kunci. Integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pemanfaatan big data harus dipercepat. Data yang akurat, mutakhir, dan menyeluruh akan menjadi fondasi bagi kebijakan yang lebih presisi dan adaptif. Tanpa itu, program sosial berisiko salah sasaran.
Selain itu, metodologi garis kemiskinan juga perlu dievaluasi. Selama dua dekade terakhir, pola konsumsi masyarakat telah berubah. Internet, misalnya, kini bukan lagi barang mewah, melainkan kebutuhan dasar bagi pelajar, pekerja, bahkan petani yang mulai terhubung dengan pasar digital. Mengabaikan perubahan ini membuat ukuran kemiskinan bisa kehilangan relevansi.
Tantangan terbesar menjelang 80 tahun kemerdekaan adalah ketimpangan antarwilayah. Jika Jawa dan Sumatera konsisten menurunkan kemiskinan, maka Indonesia Timur masih tertinggal jauh. Tiga dari sepuluh penduduk Papua Pegunungan masih hidup miskin. Artinya, keberhasilan Indonesia tidak hanya diukur dari rata-rata nasional, tetapi juga dari seberapa kecil jurang antara wilayah maju dan tertinggal.
Di sinilah arti penting perayaan 80 tahun merdeka. Capaian penurunan kemiskinan adalah kabar baik, tetapi lebih dari itu, ia adalah tanggung jawab kolektif. Menurunkan angka kemiskinan bukan sekadar target statistik, melainkan bagian dari mewujudkan janji kemerdekaan yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, tanpa kecuali.
Menjelang satu abad Indonesia pada 2045, perjalanan masih panjang. Tetapi, capaian hari ini memberi harapan bahwa bangsa ini berada di jalur yang benar. Statistik kemiskinan bukan hanya penanda progres, melainkan juga kompas moral yang mengingatkan kita. Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari kemiskinan dan ketertinggalan.
Memasuki usia 80 tahun adalah saatnya Indonesia memastikan pemulihan ekonomi benar-benar inklusif dan berkelanjutan. Agar pada saat seratus tahun nanti, kemerdekaan tidak hanya diperingati dengan upacara, tetapi juga dirasakan dalam kehidupan nyata setiap warga dari kota besar di Jawa hingga pelosok Papua.
*) Nuri Taufiq dan Lili Retnosari merupakan Statistisi di Badan Pusat Statistik (BPS)



