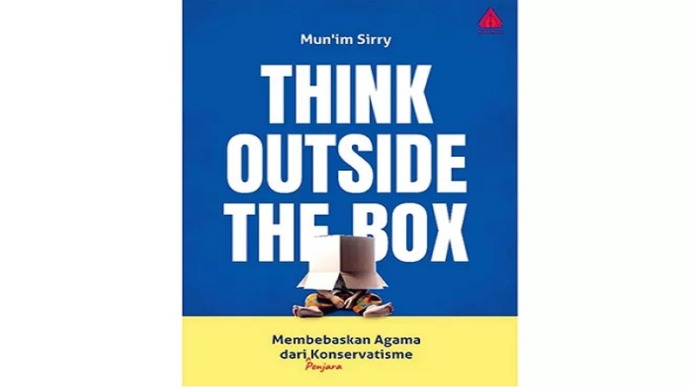Oleh MOH. ROFQIL BAZIKH*)
—
Mun’im Sirry memermak kembali tradisi keislaman yang berimplikasi pada hubungan lintas iman.
MUSTAFA Akyol di bagian pemungkas bukunya, Reopening Muslim Minds (2021), mencuplik metafora Cincin Nathan. Ini merupakan fragmen salah satu drama terkenal kepunyaan sastrawan Jerman Gotthold Ephraim Lessing (m 1781).
Sebuah drama bertajuk Nathan de Wise yang oleh Akyol dianggap mengampanyekan toleransi beragama. Metafora cincin ini mengilustrasikan tiga cincin berharga yang masing-masing mewakili agama Abrahamik.
Dari tiga cincin tersebut, hanya satu yang asli. Kendati demikian, orang yang memakainya tidak akan pernah tahu keasliannya. Hingga suatu saat datang Sang Juru Penengah (Tuhan) untuk mengungkapkan kebenaran yang hakiki.
Seminimnya, dua poin penting dapat diambil dari kutipan Akyol atas drama tersebut. Pertama, manusia, betapapun luar biasanya, tidak akan sampai pada taraf menjadi juru bicara Tuhan
–meminjam istilah yuris Khaled Abou El Fadl.
Kedua, terkait dengan kebenaran dan keselamatan komunitas religius lain. Poin terakhir ini memang memantik perdebatan sengit musabab menusuk ke jantung pertahanan teologis. Semua mengerti bahwa gereja mempunyai doktrin yang masyhur extra ecclesiam nulla salus (tidak ada keselamatan di luar gereja). Demikian juga dalam tradisi Islam dikenal hal senapas dengan itu.
Ihwal keselamatan sejatinya bukan topik pokok Mun’im Sirry dalam buku ini. Dia lebih banyak mendiskusikan ragam topik dalam studi Islam. Saya pikir, dua bukunya yang lain, Polemik Kitab Suci (2013) dan Koeksistensi Islam-Kristen (2022), cukup ekstensif membahas hal itu.
Saya melihat upayanya untuk memermak kembali tradisi keislaman yang berimplikasi pada hubungan lintas iman. Ini tampak dalam empat bab yang berkelindan erat dengan komunitas religius lain (Kristen). Mulai tafsir dan Alkitab, nikah beda agama, pluralisme agama, hingga gagasan pluralisme Wilfred Cantwell Smith.
Dalam hal ini, saya memosisikannya hendak memikirkan ulang (rethinking) pertanyaan yang selama ini tak diajukan. Kiranya tulisan Smith dan Pertanyaan yang Tak (Lagi) Ditanyakan (hal 348) mengekspresikan kesarjanaan Mun’im sendiri.
Dia dengan lugas mengakui telah mengamalkan maujud yang menjadi keprihatinan Smith setengah abad lalu. Bahwa tidak sedikit umat beragama yang enggan mempertanyakan hal-hal yang semestinya dikonfirmasi ulang. Termasuk di antaranya ihwal ketidakkeselamatan dan kebenaran komunitas religius lain yang diterima begitu saja.
Ikhtiar memikirkan ulang pemahaman agama tentu tidak semulus membalikkan telapak tangan. Ada tantangan dan kompleksitas yang oleh Mun’im tidak pernah diabaikan. Terkait term yang terakhir, menurutnya memang semacam aturan main dalam kesarjanaan dalam melihat persoalan.
Alih-alih melakukan reduksi dan simplifikasi, di banyak bukunya dia senantiasa berujar bahwa sebuah persoalan lebih kompleks dari yang sekilas tampak. Itu tergambarkan, misalnya, dalam Pluralitas Pluralisme Agama (hal 308). Dalam temuannya, dia dengan tegas menyatakan pluralisme agama tidaklah monolitik, melainkan berdiri di atas ragam tipe.
Berdasar itu pula, dia meng-counterattack pihak yang menentang pluralisme agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hemat Mun’im, fatwa yang dikumandangkan oleh MUI mengandung asumsi yang keliru.
Tiga poin penting pijakan MUI menjadi titik tembaknya, lebih-lebih soal relativisme agama. Tidak hanya silap, apa yang dianggap MUI juga Bukan Pluralisme (hal 315).
Terus terang, dia tergolong sarjana yang berani mengingat MUI sangat artikulatif dalam bidang teologi. Menyitir ungkapan Syafiq Hasyim (2020), bahkan ormas segigantis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah seakan memberikan kuasa penuh kepada MUI menyangkut persoalan teologi.
Kendati begitu, kritik-kritik Mun’im hendaknya tidak dibaca dalam kerangka bahwa imannya sedang berkurang. Kerja-kerja intelektualnya ini sepantasnya dipisahkan dari iman yang sangat personal.
Hanya dengan begitu kesarjanaan studi Islam di tanah air akan semakin semarak tanpa waswas dituding murtad. Membahas murtad, saya jadi ingat tulisan Ulil Abshar Abdalla 21 tahun lalu, Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam. Seolah repetisi, Mun’im sekali lagi hendak menyegarkan kembali pemahaman agama. Ia mengerti bahwa gagasan-gagasannya tak lazim. Tak berlebihan manakala buku ini dipungkasi epilog Gagasan Dapat Mengguncang Dunia. (*)
—
Judul: Think Outside the Box: Membebaskan Agama dari Penjara Konservatisme
Penulis: Mun’im Sirry
Penerbit: Suka Press
Cetakan: Pertama, Maret 2024
Tebal:466 halaman
ISBN: 978-623-7816-86-7
—
*) MOH. ROFQIL BAZIKH, Junior researcher di Institute of Southeast Asian Islam (ISAIs) UIN Sunan Kalijaga