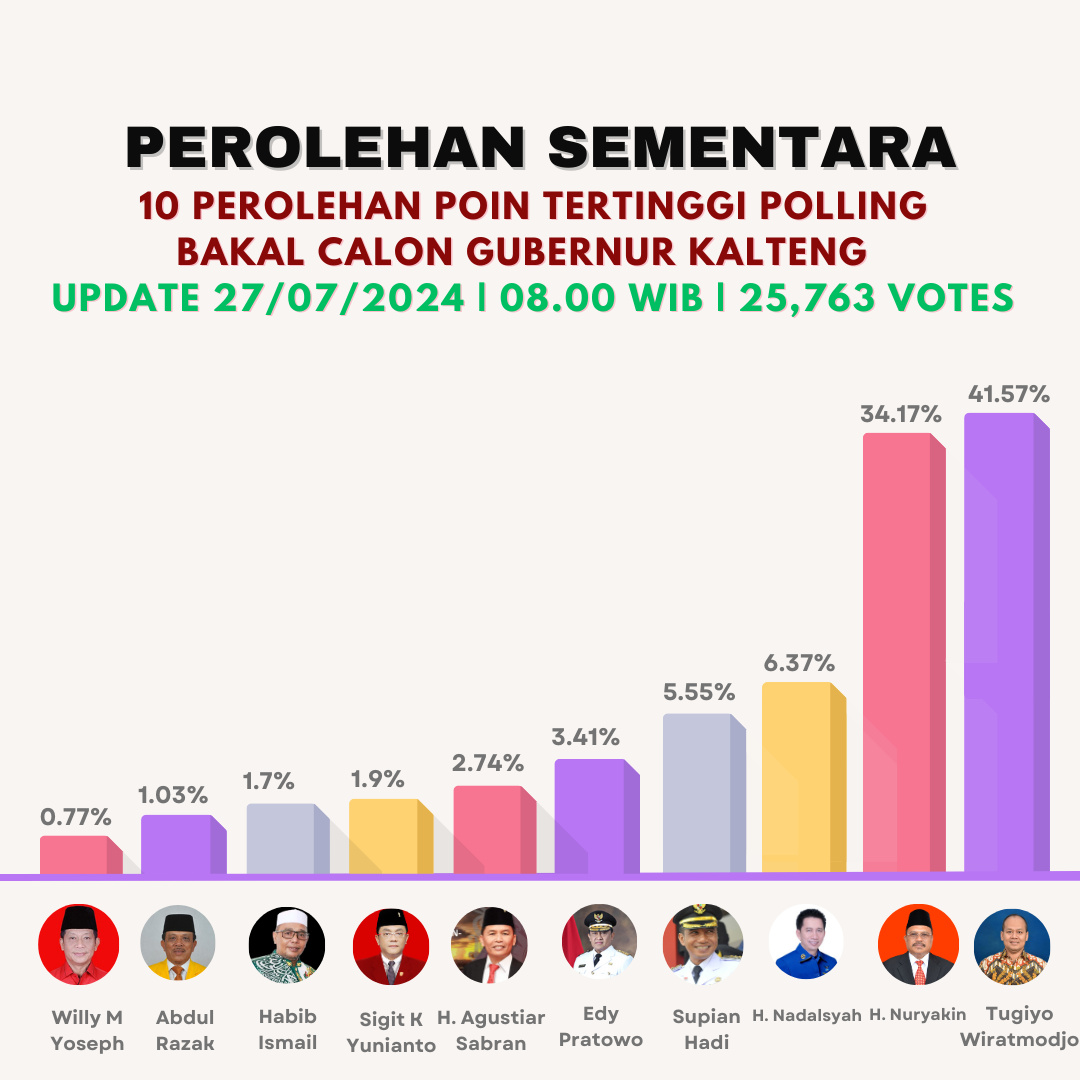”IKHTIAR! Berjuanglah membebaskan diri!” Kalimat itu pernah diucapkan RA Kartini. Dialah perempuan yang berjuang mendobrak patriarki berpuluh-puluh tahun lalu. Dia simbol perjuangan kesetaraan gender. Hari kelahirannya, pada 21 April, diperingati sebagai Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasanya. Sekaligus mengingatkan kita kembali atas cita-citanya untuk membebaskan perempuan dari belenggu patriarki.
Agaknya, setelah puluhan tahun berlalu, cita-cita mulia tersebut belum sepenuhnya terwujud. Berdasar data Global Gender Gap Report 2023, Indonesia berada di peringkat ke-87 dari 146 negara dengan skor kesetaraan gender 69,7 persen. Artinya, rapor Indonesia masih merah dan di bawah rata-rata dunia dalam hal kesetaraan gender.
Bagaimana dalam dunia kerja? Data dari Survei Angkatan Kerja BPS 2020 yang dilansir UN Women menunjukkan bahwa pada 2020, perempuan Indonesia dengan tingkat pendidikan yang setara menerima pendapatan rata-rata 23 persen lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, laki-laki mendominasi 75 persen jabatan manajerial dengan gaji 1,5 kali lebih tinggi daripada perempuan dalam jabatan yang sama.
Kondisi seperti itu terjadi karena perempuan selalu dihadapkan pada lebih banyak penghalang untuk berkarier. Mulai diskriminasi gender, keraguan yang berakar dari stigma bahwa perempuan kurang kompeten dibanding laki-laki (ingat celetukan ”perempuan pakai perasaan dan laki-laki pakai logika”?), hingga beban ganda urusan domestik.
Fenomena yang dinamakan glass ceiling ini menjadikan perempuan makin sulit meraih posisi tinggi dalam pekerjaan dan kepakaran. Bahkan, ketika perempuan telah memiliki level kompetensi dan kepakaran yang tinggi pada suatu bidang pun, ternyata tidak menjamin perempuan diberi akses yang setara untuk membicarakan pengetahuannya di ruang publik. Inilah awal terjadinya fenomena all-male panel.
Fenomena All-Male Panel
All-male panel adalah fenomena dominasi pakar laki-laki dan absennya pakar puan sebagai narasumber dalam seminar, diskusi, konferensi, dan pemberitaan media yang membuat produksi pengetahuan hanya didominasi oleh perspektif laki-laki. Homogenitas perspektif ini tentu berbahaya dengan berbagai sebab.
Pertama, hal ini dapat menciptakan blind spot dalam diskusi. Sebagai contoh, dalam diskusi mengenai pengentasan kemiskinan, absennya narasumber perempuan berarti melewatkan perspektif bahwa perempuan memikul beban pengentasan kemiskinan lebih besar akibat harus bertanggung jawab pada pekerjaan domestik dan anak sekaligus bekerja untuk membantu menghidupi keluarga (UN Women, 2021).
Contoh lain pada kasus pandemi Covid-19. Penelitian medis tanpa melibatkan peran perempuan dalam uji klinis bisa melewatkan kesimpulan bahwa obat-obatan untuk penyembuhan Covid-19 menghasilkan efek yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Kedua, dominasi pengetahuan oleh satu gender menghasilkan informasi yang tidak akurat dan berbahaya jika dijadikan sebagai dasar kebijakan. Misalnya, fenomena ”airbag bias” yang mencerminkan dampak fatal akibat pengujian airbag pada mobil hanya menggunakan model fisik laki-laki.
Pengujian itu mengabaikan perbedaan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, dari hasil studi University of Virginia di tahun 2019, kemungkinan perempuan untuk mengalami luka serius mencapai 73 persen lebih besar daripada laki-laki.
Contoh lainnya adalah ketiadaan perspektif perempuan dalam isu perlindungan sosial. Ini membuat jaminan sosial bagi perempuan disamakan dengan laki-laki. Padahal, perempuan cenderung memiliki risiko yang lebih besar. Misalnya dalam bidang kesehatan dan reproduksi.
Ketiga, ketiadaan sosok puan yang berbicara di ruang publik melenyapkan role model bagi perempuan lainnya untuk berkarier di bidang yang bersangkutan. Selain itu, dengan tanpa ketegasan menolak all-male panel akan mengerdilkan pentingnya ide, gagasan, dan suara perempuan dalam diskusi yang kontraproduktif bagi perjuangan pengarusutamaan gender yang digagas pemerintah.
Menghadirkan kegiatan yang gender-balanced pun memiliki keuntungannya tersendiri. Di antaranya menghadirkan perspektif yang beragam dan inklusif sehingga diskusi lebih kaya, berkualitas, dan kredibel; mengurangi bias dalam diskusi; menjadi model bagi para perempuan untuk maju dan merebut ruangruang berbicara; mematahkan mitos bahwa perempuan tidak sekompeten laki-laki; serta seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dunia tentang hak-hak perempuan, hadirnya pakar-pakar perempuan meningkatkan reputasi penyelenggara kegiatan.
Lalu apa yang sebenarnya menghindarkan para penyelenggara kegiatan untuk menciptakan acara yang imbang secara gender? Tentu ini hanya masalah usaha. Keberadaan pakar perempuan hanya butuh diupayakan melalui riset dan usaha untuk menjangkau mereka. Untuk memastikan hadirnya pakar perempuan, secara kolektif kita dapat melakukan hal-hal berikut.
Pertama, tim penyelenggara kegiatan harus memiliki representasi gender yang imbang dalam struktur kepanitiaan sebelum memastikan adanya gender-balance di level narasumber. Kedua, penyelenggara kegiatan dapat menghubungi komunitas atau serikat pekerja pada sektor yang bersangkutan dan meminta referensi pakar perempuan.
Ketiga, database pakar perempuan harus mulai disusun, baik oleh serikat pekerja ataupun komunitas pada sektor yang bersangkutan, dan informasi ini harus dapat diakses secara umum. Keempat, pakar laki-laki seharusnya berani menolak menghadiri kegiatan yang di dalamnya tidak terdapat narasumber perempuan.
Terakhir, secara kolektif, masyarakat Indonesia juga harus berani call-out atau mengingatkan para penyelenggara acaraacara publik yang masih mengundang all-male panel. Dan kita harus berani menolak untuk datang pada acara yang hanya menampilkan pakar laki-laki.
Itulah salah satu esensi dari perjuangan RA Kartini sebagai ikhtiar untuk memastikan kesetaraan gender. Perjuangan ini jangan sampai berhenti. Kita sebagai masyarakat harus terus-menerus memunculkan figur-figur perempuan yang berdaya di ruang-ruang publik. (*)
*) TIFARA ASHARI, Penelaah Teknis Kebijakan Kementerian Keuangan