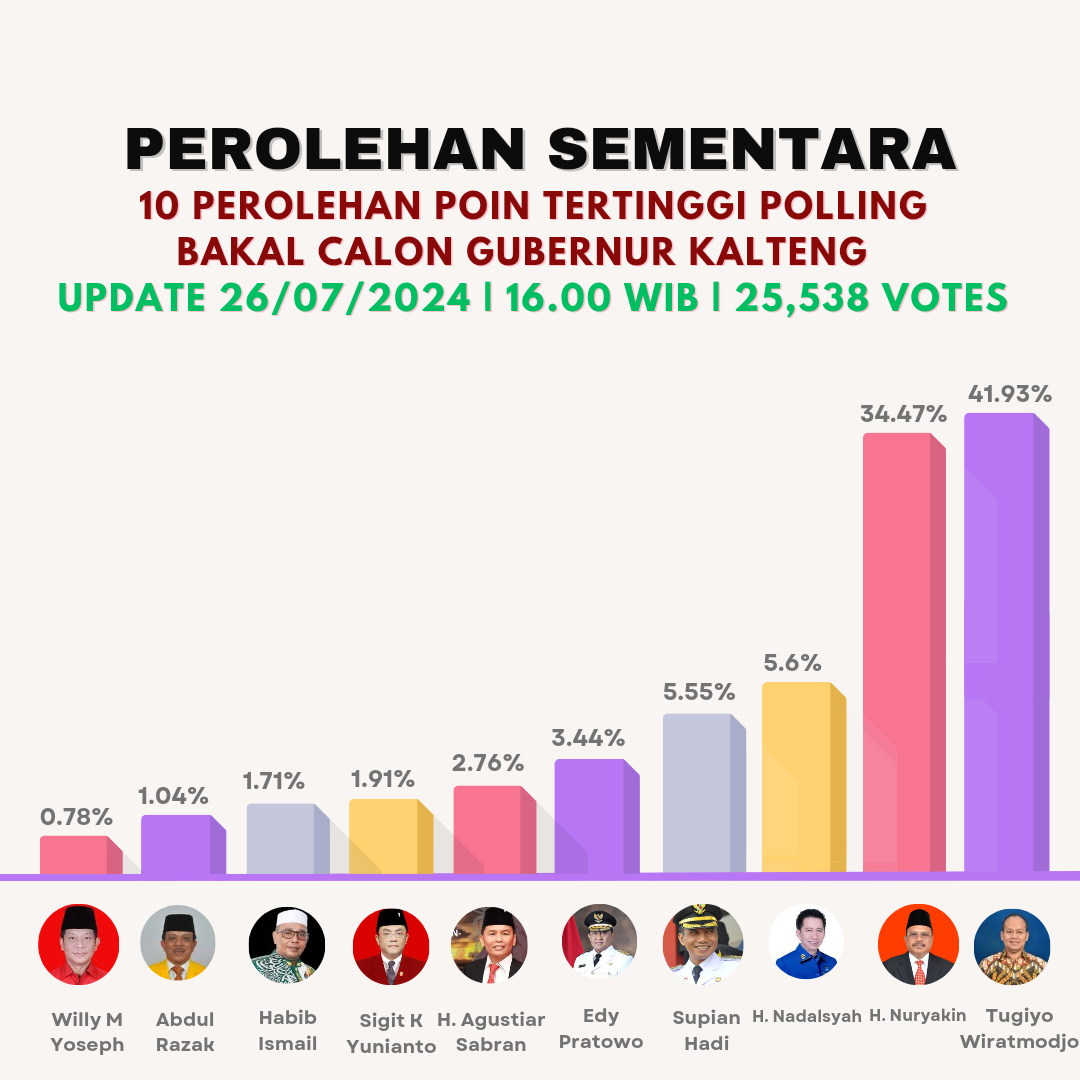BANJIR bandang di Kota Batu beberapa waktu lalu memakan korban sekian banyak orang meninggal, sementara bangunan dan lahan tersapu air bah. Kota Batu sebenarnya memiliki posisi strategis dengan disabuki gunung dan dipagari hutan. Tapi, bendung air alami tersebut kemudian jebol meluap hingga menghancurkan permukiman warga.
Banjir menjadi permasalahan klasik yang tak pernah terselesaikan secara tuntas di kota-kota di Indonesia. Ia adalah masalah kompleks yang selalu mengancam. Berbagai analisis sumber permasalahan dilakukan, berbagai saran solutif dirumuskan, dan langkah-langkah penanggulangan direalisasikan. Namun, semua seperti menemui jalan buntu. Tak mencapai jalan keluar.
Dalam kasus bencana Kota Batu, banjir dipicu oleh luapan sungai yang tak mampu menampung debit air. Saking besarnya material banjir, bencana itu juga dirasakan ratusan warga Kabupaten dan Kota Malang. Kerusakan sungai yang terjadi sejak di hulu karena hutan yang gundul dan beralih fungsi membuat ancaman lingkungan semakin nyata di depan mata. Hal itu ironis karena hutan kita adalah kekayaan luar biasa yang menyimpan berbagai macam bahan. Mulai pangan, manufaktur, hingga elemen produktif lainnya. Inilah persoalan sosial masyarakat kita.
Makna Hutan
Hutan bukan cuma wilayah ekologis, tapi juga bermakna kultural hingga religius. Nenek moyang kita dulu membuka lahan, membangun permukiman, hingga memperoleh makanan dari hasil hutan. Hutan bagi masyarakat adat Nusantara adalah arena pematangan kemampuan fisik, teknik, dan pribadi bagi inisiasi hidup kaum lelakinya. Seseorang dianggap dewasa jika sudah menjelajah hutan, menundukkan hewan liar kuat penguasa hutan, atau menangkap buruan di hutan.
Kebanyakan narasi lakon, mitos, legenda, atau babad berawal atau bersumber pada interaksi tokohnya dengan hutan. Seperti kisah sang Buddha, Ramayana, hingga Panji Inu Kertapati. Dunia pewayangan kerap menceritakan kesatria yang berjalan jauh, menemui rintangan, dan berhasil mengalahkannya. Lantas bertapa brata meski diganggu makhluk penunggu hutan, tapi mampu memperoleh aji kesaktian dan senjata ampuh.
Wayang menggambarkan isi hutan dalam wujud kayon. Tergambar pepohonan rindang dengan cabang yang merangkul dan pucuk yang tinggi menyembul dalam ukiran renik: sesuatu yang teduh. Di kerimbunan yang agung itu seperti hidup wilayah kehidupan yang lain, yang berlangsung tenang dan syahdu. Ada burung merak di antara harimau, banteng, dan kera, juga gapura dengan tempat kunci berbentuk teratai. Simbolisme imaji harmoni secara horizontal dan vertikal.
Dalam sufisme, hutan adalah wahana dan wacana kesatuan dengan Tuhan. Candra Malik (2015) menyebut hutan sebagai kumpulan pohon yang mengajarkan kepada manusia bahwa untuk hidup, kita harus mengakar dan menunjang dari mulai batang, dahan, ranting, daun, bunga, sampai buah. Akar menyerap air, yang merupakan sumber kehidupan. Bahwa untuk hidup, kita harus kukuh laksana batang pokok, menjaga dahan-ranting agar tak mudah lapuk dan patah, serta menyerap energi semesta seperti dedaunan terhadap sinar matahari. Bahwa untuk hidup, kita memberikan yang terbaik sebagaimana bunga. Tak hanya elok dipandang, tapi juga sedap aromanya.
Bahwa untuk hidup, seperti pohon, kita pada akhirnya berbuah, yang di dalamnya terkandung biji yang tak lain adalah benih bagi kehidupan berikutnya. Dari pohon kita belajar kapan pun kita pasti kembali ke tanah. Bisa karena diterpa angin dan gugur, bisa pula roboh karena usia. Maka jika pepohonan ditebang sembarangan dan tidak ada upaya menanam kembali pohon-pohon baru, sesungguhnya kita telah memadamkan pelita hidup.
Darurat
Itulah yang terjadi saat ini. Kita mengalami kondisi darurat lingkungan hidup. Bencana yang terjadi menjadi refleksi bahwa bencana itu bukan murni fenomena alam tanpa campur tangan manusia. Dalam perspektif etika lingkungan, bencana alam bukan masalah teknis, melainkan krisis moral yang tidak hanya mengenai perilaku manusia terhadap lingkungan. Tapi juga tentang relasi di antara semua kehidupan alam semesta. Aktivitas manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja dan dilakukan secara terus-menerus, dapat memicu atau mempercepat terjadinya bencana.
Hal itu terjadi karena kita memaknai hutan dan alam lingkungan sekitar sebagai objek materialisasi ekologi. Perluasan dan pengalihan lahan dilakukan tanpa kompromi, yang mengakibatkan degradasi lingkungan, kepunahan aneka jenis flora dan fauna, merebaknya konflik (bukan cuma sosial, tapi juga antara manusia dan hewan), hingga kerugian negara. Banjir lumpur yang terjadi menandai tutupan lahan yang kurang.
Dalam perspektif etika lingkungan, terjadi krisis moral perilaku manusia terhadap lingkungan. Kita melupakan dimensi kehidupan elemen penyusun ekosistem, yang mengandung pola interaksi kausalistik sekaligus komplementer dalam jejaring organisme. Akibatnya, Indonesia berubah dari mega diversity menjadi mega extinction. Keserakahan eksploitatif dan orientasi bisnis manusia tanpa memperhitungkan kerugian ekologis di masa mendatang.
Untuk itu, paradigma pragmatis yang ternyata menimbulkan kenyataan kontraproduktif bagi ekosistem lingkungan ini harus dihentikan dan diubah perspektifnya. Pengetahuan dan kesadaran ekologis tentang dampak lingkungan harus ditegakkan, bukan dikompromikan. Tapi, justru menjadi visi yang harus dikedepankan. Orientasi eksplorasi alamnya bukan eksploitatif, tapi menyelamatkan lingkungan.
Dengannya, kita tidak menciptakan hantu yang mengancam kehidupan. Hutan adalah wahana simbolis kehadiran Tuhan dengan anugerah dan keajaiban yang tersimpan di dalamnya. Terlebih, sebagai manusia bertuhan dan beragama, merawat semesta adalah kesadaran hayati bahwa manusia bukan semata-mata khalifah yang bertugas ’’menaklukkan dan menguasai dunia’’, tapi juga sebagai titah yang wajib memayu hayuning bawana. Manusia harus menyadari bahwa mereka pun adalah bagian dari dunia yang dipeliharanya sendiri. Jadi, mereka juga harus menanamkan kesadaran untuk hidup dalam harmoni dengan dunia yang didiaminya. (*)
*) PURNAWAN ANDRA, Analis sejarah dan pamong budaya pada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek