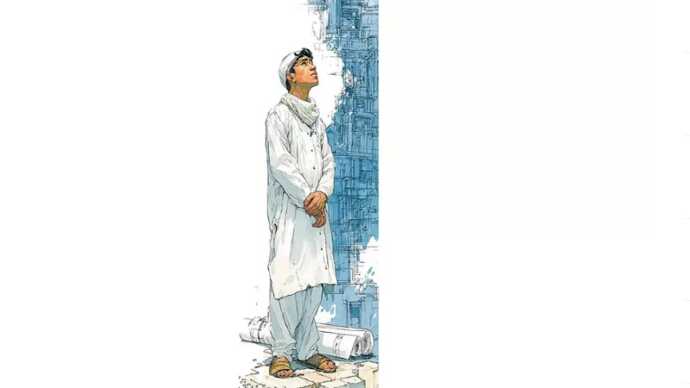Dalam sepekan terakhir, kabar duka menyelimuti dunia pesantren. Gedung di kompleks Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk dan memakan banyak korban. Para santri yang seharusnya belajar dengan tenang justru harus menanggung luka, bahkan kehilangan nyawa.
Peristiwa itu bukan hanya tragedi lokal, melainkan juga pukulan keras bagi wajah pendidikan pesantren di Indonesia. Sebab, di balik runtuhnya bangunan tersebut, tersembunyi realitas lama yang sering kita abaikan, lemahnya standar pembangunan, tradisi pengelolaan seadanya, dan kecenderungan mengandalkan niat baik tanpa diimbangi profesionalitas.
Tradisi Swadaya
Sejak awal, pesantren tumbuh dari budaya swadaya. Ada semangat kiai, ada tanah wakaf, lalu berdirilah pondok. Santri ikut membangun, masyarakat menyumbang, alumni patungan, dan setahap demi setahap gedung berdiri.
Model itu melahirkan ribuan pesantren di pelosok Nusantara tanpa harus menunggu intervensi pemerintah. Inilah kekuatan pesantren yang disebut Gus Dur sebagai lembaga pendidikan yang memiliki “kemandirian”.
Namun, dalam kemandirian itu terkandung pula kerentanan. Banyak bangunan pesantren yang berdiri tanpa rencana teknis yang jelas, tanpa desain arsitektur yang memenuhi standar keamanan, bahkan sering tanpa keterlibatan insinyur atau pengawas konstruksi.
Hasilnya, bangunan bisa selesai, tetapi kualitasnya rapuh. Di banyak tempat, kita masih menjumpai asrama bertingkat yang dibangun seadanya, ruang kelas yang sempit tanpa ventilasi memadai, bahkan instalasi listrik yang tidak aman.
Tradisi roan, yaitu keterlibatan santri dalam pekerjaan fisik mulai membersihkan lingkungan hingga ikut mendirikan bangunan, juga menyimpan persoalan. Di satu sisi, roan merupakan sarana pendidikan karakter, melatih kebersamaan, tanggung jawab, dan jiwa gotong royong.
Namun, ketika roan diterapkan untuk pembangunan fisik yang semestinya membutuhkan tenaga profesional, di situlah problem muncul. Santri yang tidak terlatih kerap diminta membantu mengangkut material, mencampur semen, bahkan ikut memasang bata. Hasil kerja memang terasa “ikhlas”. Namun, keselamatan dan ketahanan menjadi masalah berikutnya.
Kita jarang mempertanyakan itu. Seolah yakin bahwa niat baik sudah cukup untuk menegakkan tembok. Padahal, keselamatan tidak lahir dari keikhlasan semata, tetapi dari keahlian dan disiplin standar. Tragedi di Al-Khoziny menyadarkan kita bahwa romantisme gotong royong tidak boleh lagi mengorbankan nyawa santri.
Pesantren sering dibangun dengan spirit “iman dan ikhlas”. Sumbangan masyarakat, tenaga santri, dan restu kiai menjadi fondasi utama. Namun, harus diakui, iman tidak cukup untuk membuat bangunan kokoh. Ikhlas tidak bisa menggantikan analisis struktur. Doa memang menenangkan, tetapi tidak bisa menggantikan fungsi besi bertulang yang dipasang sesuai dengan perhitungan insinyur.
Kita bisa belajar dari dunia pendidikan formal yang dikelola negara. Sekolah negeri wajib mengikuti standar bangunan gedung pendidikan. Ada peraturan teknis, ada mekanisme pengawasan, dan ada prosedur perizinan. Jika pesantren ingin tetap menjadi pilar pendidikan nasional, standar keselamatan serupa seharusnya berlaku. Tidak adil jika gedung sekolah negeri diperiksa ketat, sedangkan ribuan santri di pesantren dibiarkan tinggal di asrama yang rawan runtuh.
Tragedi Al-Khoziny merupakan alarm keras bahwa pendekatan lama sudah tidak bisa dipertahankan. Pada titik ini, slogan pesantren al-muhafazatu alal qadim as-salih menjaga tradisi lama yang baik dan wal akhdzu bil jadid al-aslah menemukan momentumnya. Pesantren tidak bisa lagi bersembunyi di balik kalimat “ini tradisi pesantren” atau “semua dijalankan dengan keikhlasan”.
Tradisi yang sudah tidak relevan harus diganti dengan kebaruan yang memiliki maslahat lebih besar. Keselamatan santri harus ditempatkan sebagai prioritas mutlak, bukan sekadar urusan tambahan.
Hikmah
Dalam tradisi pesantren, kita selalu percaya bahwa semua ada hikmahnya. Karena itu, musibah di Al-Khoziny harus menjadi pelajaran bagi seluruh pesantren di Indonesia.
Salah satu ikhtiar ke depan adalah melakukan audit bangunan pesantren sebagai pengejawantahan atas prinsip darul mafasid muqadamun ala jalbil mashalih (meminimalkan korban di tempat lain). Pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga Kementerian Agama harus berkolaborasi untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan kondisi fisik pesantren.
Bangunan yang tidak memenuhi standar harus segera diperbaiki, diperkuat, atau bahkan diganti. Biaya yang muncul jangan dianggap sebagai beban, melainkan investasi keselamatan.
Tragedi Al-Khoziny telah mengajarkan bahwa kita tidak bisa terus mengabaikan aspek keselamatan. Jangan sampai tragedi itu hanya jadi berita sesaat, lalu hilang dari ingatan. Jangan sampai korban yang jatuh hanya diperingati dengan doa tanpa melahirkan perubahan nyata.
Pesantren adalah mercusuar pendidikan Nusantara. Namun, mercusuar itu hanya bisa berdiri kokoh apabila fondasinya kuat. Fondasi itu bukan hanya berupa iman dan ikhlas, melainkan juga standar keselamatan, tata kelola modern, dan kesadaran bahwa menjaga nyawa santri adalah ibadah yang mulia. (*)
*) Ahmad Munji, doktor dari Universitas Marmara, Istanbul, Turki; Alumnus Pesantren, Al-Hikmah 2 Benda, Brebes