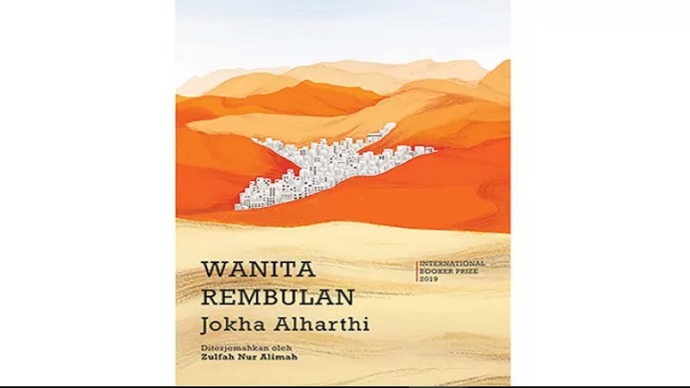Tiga generasi perempuan Oman dalam karya ini setidaknya jadi potret bagaimana perempuan sering kali menjadi gender kedua dalam lingkungan patriarki.
NOVEL dengan judul asli Sayyidat Al-Qamar ini terbit kali pertama dalam bahasa Arab pada 2010, kemudian mendapatkan atensi luar biasa dari dunia internasional ketika memenangi International Booker Prize 2019 untuk edisi terjemahan Inggris, Celestial Bodies. Semenjak itu karya Jokha Alharthi ini telah terbit dalam lebih dari 20 bahasa.
Novel berlatar Oman yang ditulis oleh pengajar Universitas Sultan Qaboos, Muscat, itu kini hadir dalam bahasa Indonesia dalam judul Wanita Rembulan (Moooi Pustaka, 2024). Jokha meminjam kisah 3 perempuan dari 3 generasi berbeda untuk mengungkit ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan perempuan.
Salimah, sebagai generasi pertama, diam-diam menjadi korban keculasan Azzan, suaminya, yang kerap menjalin hubungan rahasia dengan perempuan yang dicandra sebagai Rembulan dalam novel. Azzan dan Rembulan suka bermesraan saling berbalas puisi romantis.
Rembulan berbaring di sampingnya di atas pasir. Berbantal tangan masing-masing, mereka meratapi rasi bintang ursa minor yang tampak jelas pada musim seperti ini. (hal 112)
Perempuan pada generasi selanjutnya, anak Salimah dan Azzan, yakni Mayya, Asma, dan Khawla. Tiga perempuan tersebut mengalami ketidakadilan sebagai perempuan yang berbeda-beda, paling pokok tentu bagaimana mereka dan perempuan Oman pada umumnya tidak memiliki kebebasan dalam menentukan siapa yang akan menjadi pendamping hidup.
Mayya digambarkan sangat pendiam dan sehari-hari menghabiskan waktu di depan mesin jahit, menikah dengan Abdullah, meski Abdullah bukan lelaki yang dicintainya. Dalam doanya bahkan Mayya berdoa: ”Tuhan Yang Maha Agung, aku tak menginginkan apa pun selain melihatnya. Tuhan Yang Maha Agung, aku tak ingin ia melihat ke arahku, tetapi aku ingin melihatnya.” (hal 1)
Asma si anak kedua yang digambarkan sangat menyukai membaca dan buku nyatanya menerima pinangan salah satu anak seorang imigran. Dan, yang justru memiliki porsi tidak banyak dibanding dua saudara perempuan tuanya, Khawla, menolak semua pinangan lelaki.
Dia menunggu kekasihnya, Nasir, yang pergi ke Kanada dan kelak pulang memikul kekalahan –gagal studi dan dikucilkan sosial. Khawla sejatinya memiliki patron sebagai perempuan gigih memperjuangkan apa yang dikehendaki, sayang dalam cerita nasibnya tak ubahnya saudara lainnya: harus menjumpai kekalahan.
Generesi ketiga, London –anak sulung Mayya dan Abdullah, meski tidak lagi tinggal di Oman, tetap mengalami kekalahan dan sakit oleh lelaki. London harus bercerai dari suaminya.
Tiga generasi perempuan Oman itu setidaknya jadi potret bagaimana perempuan sering kali menjadi gender kedua dalam lingkungan patriarki. Perempuan muda, misalnya Asma, tidak diperkenankan ikut menimbrung dalam obrolan perempuan-perempuan dewasa.
Ketika lepas melahirkan dan masih dalam masa nifas, Mayya dilarang makan bersama orang-orang sebab najis. Dia harus makan terpisah. Mayya pun sejatinya tidak diperkenankan memberi nama kepada jabang bayinya, sebab nama adalah prerogatif suami. Maka ketika anak perempuan sulungnya ia beri nama London, Mayya ditegur keras oleh banyak pihak. ”Adakah orang yang menamai putrinya London? Itu nama kota, kota orang-orang Kristen.” (hal 7)
Ketimpangan lain yang sangat kentara adalah hanya laki-laki yang diperkenankan pergi jauh demi pendidikan. Dua contoh Abdullah, suami Mayya, dan Nasir, lelaki pujaan Khawla. Dua lelaki ini boleh berkelana hingga Mesir dan Kanada –sedang perempuan kembali mengurusi urusan domestik.
Pembagian peran berbasis gender inilah yang dikritik banyak aktivis perempuan. Salah satu buku Betty Friedan yang sangat terkenal, The Problem That Has No Name, telah menunjukkan gejala demikian dalam kehidupan perempuan Amerika pasca-Perang Dunia II.
Dalam budaya Indonesia sendiri, kita kerap menyebut perempuan sebagai simah, isi rumah atau yang sedikit lebih jamak orang rumah, untuk merujuk kepada istri dan ibu yang terkungkung institusi bernama rumah dan keluarga. Itu yang dilukiskan dengan bergelora oleh Jokha dalam novel ini. Selama tiga generasi perempuan selalu mengalami perlakuan tidak setara. Di tengah perubahan sosial Oman nyatanya perkara demikian telah menjadi laten.
Mayya bahkan menjadikan diam dan tidur sebagai suaka di tengah riuhnya orang-orang sekitar. Tidak lain disebabkan bersuara sekeras apa pun, suara perempuan tetap akan diredam oleh adat tradisi juga agama.
Jokha juga menyinggung bagaimana sistem perbudakan di Oman yang mulai ditinggalkan, meski bagi beberapa orang itu laten dan tanda kelas seseorang. Sebagai contoh ayah Abdullah yang seorang saudagar masih saja merasa memiliki hidup Zarifa dan seluruh keturunannya sebagai budak. Latennya iklim rasisme dan perbudakan jelas tidak mudah sekali tiris ketika pemerintah sudah melarang perbudakan.
”Apa urusannya dengan pemerintah? Sajar itu budakku, bukan milik pemerintah, mereka tidak berhak memerdekakannya. Aku membeli ibunya, Zarifa, dengan dua puluh keping perak.” (hal 13)
Novel ini sejatinya sangat ringkas, menceritakan sebuah keluarga dengan cabang-cabang kisah yang tidak kalah seru dinikmati. Jokha mengganti-ganti point of view setiap tokoh. Bukan sekadar bermain-main teknik penulisan, tetapi juga menjadi legitimasi bahwa perkara ketimpangan ini –baik soal perempuan maupun perbudakan– sama dirasakan oleh banyak pihak.
Ketimpangan atas gender perempuan sekaligus maraknya sistem perbudakan dan rasisme menjadi pokok kentara dalam novel ini. Wanita Rembulan sebagai satu bukti bagaimana kemanusiaan kadang berada di tubir dan harus hadir suara-suara berani untuk melantangkannya. Melantangkan yang timpang, meski itu berasal dari belahan jauh dari kita. Sebab demikianlah fungsi sastra. (*)
—
JUDUL: WANITA REMBULAN
Penulis: Jokha Alharthi
Penerjemah: Zulfah Nur Alimah
Penerbit: Moooi Pustaka
Edisi: Pertama, Februari 2024
Tebal: 248 halaman
ISBN: 9786238837632
—
*) TEGUH AFANDI, Editor buku