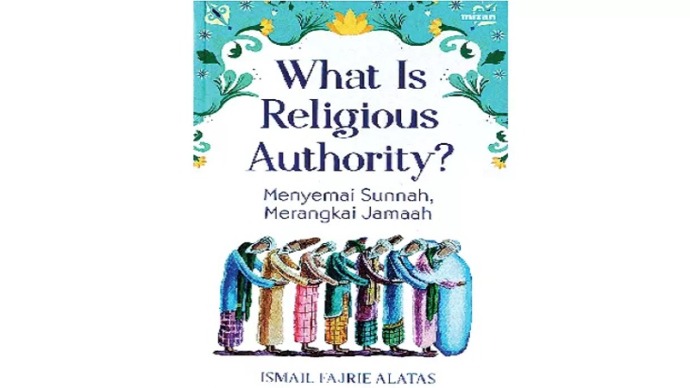Oleh M. MUSHTHAFA
Dengan gaya bertutur yang sangat nyaman dibaca, buku ini mendedahkan infrastruktur kerja artikulasi Habib Luthfi. Ismail Fajrie Alatas menawarkan cara pandang baru untuk melihat dinamika otoritas keagamaan.
BUKU yang ditulis Ismail Fajrie Alatas ini mengangkat tema otoritas keagamaan dengan tesis baru yang menarik. Bukannya menekankan otoritas keagamaan pada teks-teks keagamaan atau karisma sosok tertentu, buku ini menyatakan bahwa otoritas keagamaan merupakan hasil kerja artikulasi yang dilakukan secara berkelanjutan, yakni bagaimana seorang aktor menerjemahkan sunah dan merangkai jemaah sehingga dia mendapatkan pengakuan dan kepatuhan tanpa paksaan.
Secara konseptual, buku ini menempatkan Islam sebagai tradisi diskursif sebagaimana digagas Talal Asad, yang tidak hanya mengaitkan Islam dengan kitab suci atau tradisi tekstual, tetapi juga terkait dengan bentuk praktik sosial yang berubah-ubah yang bergerak dengan mencari landasan pada masa lalu fondasional. Karena itu, buku ini menolak gagasan Islam yang esensialistik yang bersifat akultural.
Buku ini menempatkan Islam sebagai realitas sosiologis, sebagai ”hasil dari suatu ikhtiar budi daya lahan sosial yang idealnya terus tumbuh dan berfungsi sebagai realisasi pranata norma-norma yang dahulu pernah ditegakkan oleh nabi”.
Istilah kerja artikulasi (articulatory labor) menggambarkan kalibrasi aneka unsur pembentuk komunitas Islam yang bersifat konkret, relasional, dengan moda kerja beragam, yang pada satu titik dapat membentuk paradigma artikulasi tertentu. Berbeda dengan ”karya/cipta” (work), kerja artikulasi merupakan reproduksi terus-menerus dan berulang yang memanfaatkan infrastruktur dan kerja politik tertentu.
Dengan kerangka konseptual seperti ini, buku ini mengkaji kerja artikulasi Habib Luthfi dalam membangun jemaahnya. Namun, sebelum itu Alatas memberi gambaran latar kerja artikulasi Habib Luthfi yang terkait dengan bentuk dan perkembangan komunitas muslim di Nusantara.
Kerja artikulasi dapat berlangsung pada komunitas yang beraneka ragam seperti tarekat, perdikan, keraton, atau wilayah suci yang di daerah Hadramaut disebut hautha. Alatas menyinggung Dipanagara yang merangkai komunitas dengan menerjemahkan masa lalu kenabian dengan melihat peran nabi sebagai prototipe mistikus sejati. Namun, Dipanagara memadukan kerja artikulasinya dengan cara pandang dunia roh para leluhur Jawa sehingga melahirkan artikulasi sunah yang khas.
Alatas membandingkannya dengan beberapa ulama Hadrami yang di antaranya mengembangkan komunitas berbasis teks seperti yang dilakukan Abdallah bin Alawi Al-Haddad (w 1720) yang kemudian menjadi cukup paradigmatik di Nusantara. Kinerja Haddadiyah dilakukan dengan menerjemahkan Islam yang mudah diakses orang kebanyakan dengan mengobjektifikasi ajaran nabi dalam teks teologi, fikih, dan wirid yang mudah dipahami. Otoritasnya berkaitan dengan syaikh al-ta’lim (guru ajar) yang dianggap mampu untuk mengajarkan teks dan kurikulum standar.
Ada pula moda kerja artikulasi yang disebut ”dinasti kewalian” (manshobah) yang berpusat pada masa lalu kewalian pendiri jemaah. Dinasti kewalian dipimpin munshib turun-temurun yang otoritasnya berkaitan dengan ketersambungan hubungan darah (nasab). Di Indonesia, ada setidaknya 52 haul wali Hadrami yang rutin dilaksanakan sebagai bagian dari kerja artikulasi manshobah.
Habib Luthfi berada di antara moda-moda kerja artikulasi tersebut. Otoritas keagamaan Habib Luthfi tidak terbentuk terutama melalui jalur nasab. Sebab, meski tersambung dengan Ba Alawi di Hadramaut, Habib Luthfi tidak berasal dari keluarga ulama atau wali.
Otoritas Habib Luthfi dibangun dengan mobilitas atau rihlah mencari ilmu. Mobilitas yang membelok pada Habib Luthfi ditandai dengan jejak rihlah keilmuan dan spiritualnya yang beragam yang menyerap keanekaragaman sosial-budaya lokal di Nusantara, tak hanya pada jejaring Hadrami.
Genealogi Habib Luthfi mula-mula tersambung dengan jaringan non-Ba Alawi melalui adopsi genealogis ketika ia diangkat sebagai mursyid Naqsyabandi-Khalidi-Syadzili (NKS) oleh gurunya yang berdarah Jawa, Abdul Malik bin Muhammad Ilyas (w 1980).
Keragaman dan lokalitas ini berpengaruh terhadap model sunah yang dikembangkan Habib Luthfi. Pemahaman dan kepekaan Habib Luthfi terhadap kultur yang beragam memperluas ruang gerak Habib Luthfi dengan komunitas dan jemaah yang lebih beraneka. Kita tahu, Habib Luthfi menguasai ragam bahasa kromo, juga bahasa Sunda, meski dalam bahasa Arab komunikatif cukup lemah.
Setelah tinggal di Pekalongan, kerja artikulasi Habib Luthfi berhadapan dengan komunitas jemaah yang lain yang berbasis munshib atau lainnya. Misalnya, dalam berinteraksi dengan jemaah Masjid Al-Raudhah yang berkomitmen secara kaku pada bahasa Arab dan ritual Ba Alawi. Ketegangan terjadi karena Kanzus Shalawat, pusat kegiatan jemaah Habib Luthfi, berdiri tidak jauh dari masjid yang diasuh munshib ketiga Pekalongan, Habib Bagir.
Dengan gaya bertutur yang sangat nyaman dibaca, buku ini mendedahkan infrastruktur kerja artikulasi Habib Luthfi seperti praktik shuhbah (penyertaan) atau pertemuan rutin bulanan dengan jemaah, penyusunan kitab wirid, relasi dengan aktor-aktor negara atau penguasa atau bahkan Keraton Jogjakarta, juga bagaimana Habib Luthfi membangun otoritas keagamaannya dengan berusaha merekonstruksi jejaring leluhurnya melalui pembangunan makam-makam wali yang diklaim memiliki hubungan nasab.
Nilai penting buku yang ditulis associate professor di New York University ini terletak pada cara pandang baru yang ditawarkan untuk melihat dinamika otoritas keagamaan. Perspektif baru buku ini sangat berharga untuk dijadikan cara memotret keragaman komunitas-komunitas muslim di Nusantara pada khususnya yang memiliki keragaman moda artikulasi dalam mengembangkan dakwah dan komunitas masing-masing.
Keragaman model penafsiran sunah dan jemaah umat Islam di Nusantara bagaimanapun harus dilihat sebagai sebuah kekayaan budaya yang harus digali untuk dijadikan dasar dalam mengembangkan ragam dan model penghayatan keislaman yang lebih baik.
Saya yang dibesarkan dalam tradisi pesantren di Madura, misalnya, dapat merasakan betapa kerja-kerja artikulasi para kiai di pesantren sangatlah beragam dan menarik untuk didalami. Tawaran perspektif dan metodologis yang diajukan buku ini sangatlah berharga untuk dilewatkan begitu saja oleh para pengkaji Islam di Indonesia pada khususnya. (*)
—
Judul: What is Religious
Authority: Menyemai Sunnah, Merangkai Jamaah
Penulis: Ismail Fajrie Alatas
Penerbit: Bentang dan Mizan Wacana, Jogjakarta
Cetakan: Pertama, Januari 2024
Tebal: xxvii + 338 halaman
—
MUSHTHAFA, Dosen filsafat di Institut Ilmu Keislaman Annuqayah. Penerima Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) LPDP-Kemenag pada Program Doktor Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.